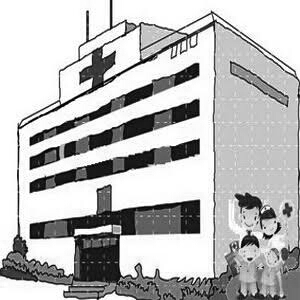Oleh Arpan Rachman*
![]() Awal datang ke Makassar, tahun 2011, saya langsung bertemu dengan dua orang Nomor Satu. Habis magrib, Pak Syahrul menerima saya bertamu. Pulangnya diberi cendera mata: tasbih. Esoknya, saya menonton klub PSM latihan di Karebosi. Di sana jumpa Pak Ilham, Penerimaan Walikota sama ramah dan hangatnya dengan Gubernur.
Awal datang ke Makassar, tahun 2011, saya langsung bertemu dengan dua orang Nomor Satu. Habis magrib, Pak Syahrul menerima saya bertamu. Pulangnya diberi cendera mata: tasbih. Esoknya, saya menonton klub PSM latihan di Karebosi. Di sana jumpa Pak Ilham, Penerimaan Walikota sama ramah dan hangatnya dengan Gubernur.
Tapi, kemudian saya merasa gatal juga. Ingin menyampaikan kritik, walau terus terang, sebenarnya sungkan. Khususnya karena dua Bapak itu, yang menyambut saya dengan senyum sejuk khas kota Angin Mamiri. Mereka sudah amat baik hati.
Maafkan ki, kodong…
“Makassar Kota Dunia” adalah kejutan pertama yang hendak saya kritisi. Menyeberang dari Sumatera ke Sulawesi, jargon ini saya hapal dari internet. Sebelum turun dari tangga kapal Lambelu, yang kini sudah tenggelam itu, saya membayangkan sebuah kota modern sesuai slogan tersebut.
Merantau ke Kota Dunia, kedengarannya lumayan hebat juga. Tentu ada standar kehidupan yang layak bagi publik di selatan Pulau Celebes. Ukurannya mungkin setara kota-kota kecil di negara-negara besar yang lebih maju dari kota asal saya sendiri, Palembang.
Itu bayangan saya semula.
Apalagi saya tidak sendirian di Makassar, sahabat karib saya sudah duluan tinggal di sini, jadi pejabat pula: Wakil Kepala Kantor Pos di bilangan Jalan W.R. Supratman, tak jauh dari Balaikota. Ia bahkan terus sekolah, tamat kuliah lanjutan di Universitas Hasanuddin.
Saya semula berpikir di kota ini akan mendapati disiplin dan keteraturan yang membuat saya bisa serius mematuhinya. Mungkin saya dapat meniru gaya hidup mendiang ayah saya: berjalan kaki 10 kilometer setiap hari. Pasti trotoarnya bagus, banyak zebra cross, durasi lampu merahnya pasti, para pengendara dengan santun melaju dan menghormati sesama pemakai jalan. Saya tentu bisa jadi pejalan kaki yang hidup sehat di Makassar.
Maka saya lakukan survei kecil-kecilan atas inisiatif sendiri. Berjalan kaki satu-dua hari sampai seminggu. Semua bayangan awal itupun rontok seketika. Trotoar lebih banyak “disewakan” kepada pedagang kaki lima. Zebra cross tidak berguna karena para pengendara lebih sering tambah ngebut apabila melihat pejalan kaki merintangi laju kendaraan mereka. Traffic light yang berkelap-kelip di tiap simpang jalan tidak sama panjang durasinya menyala. Saya selalu dicekam rasa agak takut saban hendak menyeberang jalan.
Ini hanya urusan menyeberang jalan, bayangkan!
Akhirnya saya lebih suka naik sepeda motor. Tubuh ini makin lama kesehatannya mengendur. Apalagi kebiasaan mengepulkan asap rokok tak juga bisa saya hentikan. Setiap tahun selama empat tahun pertama berkelana di Makassar, saya pasti menderita sakit sejenak. Dirawat di rumah sakit, berkisar 2-3 hari, entah kena tifus atau kecapaian. Saya jadi lebih akrab dengan Grestelina, Stella Maris, Akademis, dan Rumah Sakit Haji.
Kala terakhir saya pergi dari Makassar, yang tampak di mata ini, slogan “Makassar Kota Dunia” masih terpampang di sejumlah lokasi tempel baliho. Mungkin saya hanya keliru mengartikannya. Harusnya kalimat tidak lengkap itu disempurnakan menjadi: “Makassar adalah salah satu kota di dunia.” Dan saya tidak berhasrat memaknainya lagi.